
Kisah nyata ini tentang seorang warga India, tetapi bisa saja terjadi pada orang Indonesia, pada siapa saja. Demikian yang terjadi dan saya dengar dari sumber yang bisa dipercaya: Seorang anak laki dari keluarga menengah menunjukkan prestasi yang luar biasa sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Selalu ranking, hampir tidak pernah berada di urutan ketiga. Hanya beberapa kali ranking kedua, umumnya selalu pertama.
Di India, seorang anak brilian seperti itu sudah hampir dapat dipastikan akan diterima oleh salah satu dari sekian banyak Indian Institutes of Technology (IIT) yang tersebar di seluruh republik. Maka, pemeran utama dalam kisah ini pun mendapatkan kesempatan belajar di IIT Chennai. Di Chennai pun ia menunjukkan prestasi yang tak tertandingi. Dengan bekal B.Tech yang diraihnya, ia mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan master degree-nya di Amerika.
Dengan prestasi seperti itu, balik ke India sudah tidak menjadi opsi lagi baginya. Ia menetap di Amerika. Ya, sempat balik, nikah di Chennai. Kemudian, bersama istrinya balik lagi ke negeri Paman Sam. Semuanya berjalan lancar. Sepertinya semua sudah set. Tidak ada yang salah dalam setting hidupnya.
Orang tua di Chennai pernah berkunjung menengok anak dan cucu mereka – apa yang mereka lihat sangat memuaskan. Walau tetap tersisa pertanyaan: “Nak, apakah kamu tidak berpikir untuk kembali ke negeri sendiri, menetap di sana?” Tokoh kita tidak ingin menyakiti hati orang tua, namun jawabannya adalah tidak, walau dibungkusnya secara rapi. “Jarak antara India dan Amerika sudah tidak seberapa Pak. Apalagi teknologi masa kini memungkinkan kita berkomunikasi kapan saja. Dan, sewaktu-waktu kita akan tetap berkunjung ke India juga.”
Bunuh Diri
Tapi, tiga tahun kemudian, orang tua pahlawan kita terguncangkan oleh berita bunuh diri anak mereka bersama dengan menantu dan kedua cucu. Apa yang terjadi?
Ia menembak istri dan anak-anaknya, kemudian dirinya sendiri. Sempat pula ia meninggalkan catatan, di mana dijelaskan secara rinci, sebelum mengambil langkah tersebut, ia sudah mendiskusikan dengan istrinya. Dan mereka sepakat bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya.
Kasus dan catatan bunuh diri itu telah dipelajari oleh salah satu lembaga psikologi klinis di Amerika untuk memahami cara berpikir seorang dewasa yang berpendidikan dan dianggap cukup sukses dalam karirnya.
“The American Dream” keluarga tersebut berakhir karena kemerosotan ekonomi Amerika. Ia kehilangan pekerjaan. Selama berbulan-bulan, ia mencari pekerjaan yang pantas, yang layak – tapi tidak dapat. Pekerjaan dengan status lebih rendah dengan penghasilan jauh di bawah penghasilan sebelumnya tidak masuk akal. Sementara cicilan mulai rumah, dan segala macam gadget, yang sesungguhnya tidak dibutuhkan – berjalan terus.
Akhirnya, mau tak mau ia mesti bekerja sebagai tenaga lepasan di pom bensin. Ia merasa harga-dirinya terinjak-injak. Ia mengakhiri catatannya, “Sekarang berakhir sudah semuanya. Kami senang bahwa seluruh penderitaan kami sekeluarga akan berakhir.”
Kesalahan
Para ahli psikologi klinis menyimpulkan bahwasanya pria tersebut, telah memprogram dirinya untuk sukses. Tetapi tidak pernah melatih diri untuk menerima kegagalan, jatuh, dan bangkit kembali.
Jangan-jangan memang sistem pendidikan kita dibuat untuk meraih sukses dan tidak mendapatkan pelajaran untuk mengalami kegagalan. Jangan-jangan sebagai orangtua, kita pun sudah melakukan kesalahan yang fatal karena hanya mengharapkan anak-anak kita selalu ranking, selalu mendapatkan piala. Kita pun tidak mempersiapkan mereka untuk menerima kegagalan, kejatuhan, dan tetap bersemangat untuk bangkit kembali.
Sementara perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan gaji besar memiliki harapan besar pula. Jika harapan itu tidak terpenuhi, maka you are fired. Titik. Tidak ada tawar menawar.
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Pendidikan yang bertujuan untuk meraih keberhasilan materi semata, tanpa unsur-unsur kemanusiaan lainnya – telah terbukti gagal oleh kisah di atas. Setiap anak, setiap siswa, setiap orang, setiap karyawan, setiap eksekutif sedang berlomba. Dan, dalam setiap perlombaan yang akan keluar sebagai pemenang hanya satu hingga tiga orang – peraih nomer 1, 2, dan 3 – bagaimana dengan 97 yang tersisa?
Ah, jangan bicara tentang 97 yang tersisa. Kisah tragis di atas adalah tentang para pemenang, nomer 1 hingga 3. Lihat saja apa jadinya. Mari kita jadikan bahan renungan…..
*Anand Krishna, Humanis Spiritual, Penulis lebih dari 170 buku, Pendiri Anand Ashram (www.anandkrishna.org)
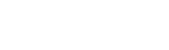
Comments